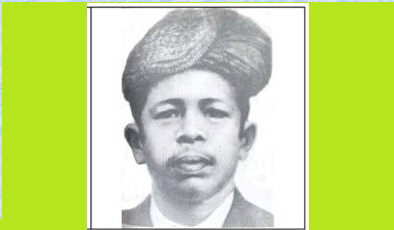Oleh: Addi Arrahman, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Abstract
Mahyudin Dt. Sutan Maharaja in Sulit Air is better known as a journalist and traditional leader. Infact, Mahyudin Dt. Sutan Maharaja, through his journalistic activities, has been the driving force forwomen’s economy in Minangkabau in the early 20th century. This is evidenced by his efforts to establish Kerajinan Minangkabau Laras Nan Dua (1907), Women’s Weaving School (1909), Vereeniging Pemadjukan Kepandaian Bertenoen (1914) and Sarikat Sekolah Tenun (1914). He was also directly involved in the creation of the Kerajinan Andeh Setia (1912), which later inspired the founding of Kakak Saijo (1913) and Andeh Sakato (1913). Through this economic movement in the weaving sector, Dt. Sutan Maharaja drives the women’s economy in Minangkabau.
Keywords: Mahyuddin Dt. Sutan Maharaja, Women’s Economy, Weaving Crafts
Abstrak
Mahyudin Dt. Sutan Maharaja di Sulit Air lebih dikenal sebagai seorang jurnalis dan tokoh adat. Padahal, Mahyudin Dt. Sutan Maharaja, melalui aktifitas jurnalistiknya, telah menjadi penggerak ekonomi perempuan di Minangkabau awal abad ke-20. Ini dibuktikan dengan upaya dia mendirikan Kerajinan Minangkabau Laras Nan Dua (1907), Sekolah Tenun Perempuan (1909), Vereeniging Pemadjukan Kepandaian Bertenoen (1914) dan Sarikat Sekolah Tenun (1914). Dia juga terlibat lansung pendirian kerajinan Andeh Setia (1912),yang kemudian menginspirasi berdirinya Kakak Saijo (1913) dan Andeh Sakato (1913). Melalui pergerakan ekonomi di bidang tenun inilah, Dt. Sutan Maharaja menggerakkan ekonomi perempuan di Minangkabau.
Keywords: Mahyuddin Dt. Sutan Maharaja, Ekonomi Perempuan, Kerajinan Tenun
PENDAHULUAN
Politik Etis merupakan arus utama kebijakan penjajah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Rifleks menegaskan bahwa orang tidak akan dapat memahami sejarah Indonesia pada masa ini tanpa mengacu kepada kebijakan tersebut. Ciri pokoknya adalah mempertemukan masalah kemanusiaan dan ekonomi sekaligus. Walaupun dalam praktiknya, kebijakan ini hanya sebatas pemanis; atau sekedar janji kemanusiaan namun tidak mewujud dalam kenyataan. Karena, ekspansi bersenjata pada akhir abad ke-19 semakin menyadarkan pihak Belanda bahwa Indonesia adalah pasar yang potensial. (M.C. Ricklefs, 2008, hlm. 327–328)
Kasus Minangkabau bisa dijadikan contoh. Setelah daerah ini berhasil ditaklukkan dengan memboncengi kelompok adat pada peristiwa paderi, terjadi perubahan yang sangat besar dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Dobbin secara baik mengurai motif kepentingan ekonomi kolonial dalam perang itu. Daerah-daerah pedalaman yang tadinya tidak terekspos, mulai mendapat perhatian karena kekayaan sumber daya alamnya (Dobbin, 2008).
Pada saat yang sama, narasi intelektual diwarnai oleh konflik berkelanjutan antara kaum tua dan kaum muda (Taufik Abdullah, 2018). Akan tetapi, kedua kelompok ini sama-sama digerakkan oleh “ide kemajuan” (the idea of progress). (Lihat pengantar Taufik Abdullah dalam buku: Navis, 1984) Itulah sebabnya, arena konflik kedua kelompok ini bergeser ke wilayah gagasan. Surat kabar menjadi media yang paling banyak merekam perdebatan ini
(Hadler, 2010; Sunarti, 2013, 2015). Sebutlah misalnya antara Mahyudin Dt. Sutan Maharaja (Pelita Ketjil, Tjahja Sumatra, Oetoesan Melajoe, Soenting Melajoe) dan Abdullah Ahmad (al-Munir). Melalui surat kabar ini, kemudian, muncullah agen baru perubahan di Minangkabau awal abad ke-20.
Seorang sarjana Belanda, B.J.O. Shrieke menyebut Mahyuddin Dt. Sutan Maharaja sebagai The Father of Malay Journalism. Keterlibatan dia sebagai jurnalis di hampir sepanjang hayatnya, adalah kontribusi pentingnya terhadap dunia pers pada awal abad ke-20 di Minangkabau. Sekalipun sering terlibat ‘adu mata pena’ dengan redaktur surat kabar lain, namun Dt. Sutan Maharaja tetap dikenal sebagai orang yang konsisten dengan ide-ide yang dikembangkannya. Baginya, semangat berkemajuan tidaklah bertentangan dengan adat Minangkabau. Sebab itu, dia menolak kelompok modernis Islam yang dianggap “peneruspaderi yang wahabi” atau kelompok sekuler yang mengagung-agung budaya barat.
Atas upaya Mahyuddin Dt. Sutan Maharaja mengangkat adat Alam Minangkabau, dia diberi julukan sebagai “Dt. Bangkik”. Taufik Abdullah menyebut dia sebagai seorang “modernis adat” melalui ide “adat democratic revolution”(Abdullah, 1972). Itulah sebabnya, surat kabar yang dipimpinnya menjadi wadah bagi kelompok adat menuangkan gagasannya, sehingga mendapat tempat tersendiri di tengah masyarakat. Sementara kaum tua dari kelompok adat tidak mendukung pergerakan perempuang, Dt. Bangkik justeru menjadi seorang feminis yang terus membela hak-hak perempuan. Soenting Melajoe, menurut Salmon, lebih tepat disebut sebagai surat kabar “feminis” dari pada “feminim”(Salmon, 1977).
Artikel ini coba mengulas dimensi lain dari sosok Mahyuddin Dt. Sutan Maharaja. Bukan sebagai seorang jurnalis atau ahli adat, melainkan sebagai seorang penggerak ekonomi perempuan di Minangkabau pada awal abad ke-20. Sejauh ini, belum ada satu tulisan pun yang secara khusus mengulas aspek ini. Salmon dan Taufik secara sepintas menyebutkan peran Dt. Bangkik dalam menghidupkan pertenunan di Minangkabau. Namun, kedua penulis ini lebih menyorot figur Dt. Sutan Maharaja sebagai seorang jurnalis dan ahli adat. Mengapa Dt. Sutan Maharaja memberikan perhatian lebih terhadap kemajuan perempuan, terutama pada aspek pendidikan dan ekonomi? Bagaimana dia melembagakan gagasannya tentang ekonomi perempuan? Studi sejarah sosial kritis terhadap pemikiran Dt. Sutan Maharaja yang tertuang dalam majalah Soenting Melajoe dan Oetoesan Melajoe, menjadi sumber penting untuk menjawab dua pertanyaan ini.
Mahyudin Dt. Sutan Maharaja; Biografi Singkat
Mahyudin Dt. Sutan Maharaja lahir di Sulit Air pada 27 November 1860. Dia berasal dari keluarga yang memegang teguh adat alam Minangkabau. Gelar Dt. Sutan Maharaja diwarisi dari kakeknya dari garis ibu yang mati di tangan paderi karena sangat memegang nan sapanjang adat. Kematian kakeknya ini, agaknya menjadi alasan pribadi mengapa Dt. Sutan Maharaja tidak menyukai gerakan pembaharuan Islam yang dibawa oleh kelompok modernis dari kaum muda. Pada surat kabar Soenting Melajoe No. 34, 1 Oktober 1920, dijelaskan:
“Dimasa padrie telah moelai ada di Alam Minangkabau ini (+ di tahoen 1805 sangat sekali pantangan padrie menjaboeng itoe hingga satoe orang toewa di Tjoemati Koto Piliang jang berbalai di Batoe Tagah namanja diperantaraan Tandjoeng Balit Soelit Air bergelar Datoe’ Soetan Maharadja Besar, Dalima Singkat jaitoe ninik Mojang sebelah keiboe daripada Datoe’ Soetan Maharadja (red. O.M.) diboenoeh oleh padri dari sebab orang toea itoe sangat sekali mengoeatkan nan sepandjang adat. Maka anak orang toea itoe bergelar Datoe’ Malakomo menoentoet bela berperang dengan padri, mati poela dalam perang itoe. Anak Datoe’ Malakomo itoe Datoe’ Bandaharo Piliang Taboeh nan Gedang sobat toean Stermeiz jang sama-sama mengalahkan Bondjol di Tahoen 1837. Anak Datoe’ Bandaharo roemah Piliang Taboeh nan Gadang itoelah Datoe’ Bandaharo Petapang roemah Sloengkang Soelit Air, dan anak beliau itoelah jang D.S.M red O.M. sekarang.
Keterangan di atas menegaskan bahwa Mahyudin Dt. Sutan Maharaja adalah “urang bajinih” di nagarinya. Atas jasa Datuk Bandaharo (Piliang Tabuah nan Gadang) melawan paderi di Bonjol dengan membawa pendekar dari Sulit Air sekitar 100-200 orang, pada tahun 1860 dia diberi jabatan larashoofd pertama Sulit Air yang kemudian digantikan oleh anaknya, Dt. Bandaharo ayah Dt. Sutan Maharaja. Akan tetapi, pada pertengahan tahun 1875, Dt. Bandaharo berhenti menjadi larashoofd sebagai bentuk penolakannya terhadap klaim pemerintah atas tanah ulayat yang dimuat dalam staatblad 1874 no. 94. Keadaan ini menyebabkan Dt. Sutan Maharaja gagal dikirim ke Belanda sebagaimana yang dijanjikan oleh kolonel de Rooy van Zuiderwijn pada tahun 1873 saat berkunjung ke Sulit Air meninjau keberhasilan Dt. Bendaharo sebagai larashoofd dan kepandaian bertenun perempuan Sulit Air (Soenting Melajoe, No. 33, 17 September 1920).
Mahyuddin Dt. Sutan Maharaja termasuk generasi pertama yang berpendidikan barat. Berkat kedekatan ayahnya dengan pihak Belanda, pada tahun 1872, dia dan 3 orang temannya dari Sulit Air, masuk sekolah Belanda di Padang. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian, ketiga temannya dikeluarkan dari sekolah karena sering berkelahi dengan anak anak Belanda. Sedangkan Dt. Sutan Maharaja terus melanjutkan sekolahnya (Soenting Melajoe, No.33). Gagal melanjutkan pendidikan ke Belanda, pada 17 Februari 1876, dalam usia 14 tahun, Dt. Sutan Maharaja magang di kantor hoofddjaksa di Padang. Muhammad Thaib gelar Sutan Maharaja adalah guru yang berjasa membimbing dia saat itu. Karakternya yang rajin, rendah hati dan adil, secara cepat menaikkan karirnya. Selain itu, perhatiannya terhadap ilmu sangat tinggi. Saat ada seorang guru mengaji dari Payakumbuh datang ke Padang, Mahyuddin Dt. Sutan Maharaja juga belajar mengaji.
“…sementara mendjelang itoe koe ada dalam satoe bilik belakang beladjar mengadji qor’an kepada seorang kari qor’an jang datang dari pajakoemboeh, engkoe Noenang orang seboetkan gelar beliau.
Engkoe Noenang itoe walaupoen soedah toewa tetapi lidah beliau amat fasihat mengadji qor’an dengan bertadjwid hingga beliau adjarkan koe bertajwit mengaji qor’an.
Beliau adjarkan kepadakoe bagaimana jang idgham; idgram ma’groena, idgram mitzlaini, idgram takribbaini dan lain lain hingga dapatlah olehkoe mentjatjat kalau orang mengadji qor’an jang tak meatjoehkan tadjwid.” (Seonting Melajoe, No. 38, 29 Oktober 1920)
Pada 1 Agustus 1879, dia sudah menjadi juru tulis hoofdjaksa dengan gaji f20 per bulan. Gajinya terus naik, seiring dengan karirnya sampai menjadi jaksa di Indrapura tahun 1882 (6 bulan) dan selanjutnya di Padang (1883) dan Pariaman. Dengan demikian, dalam usia yang cukup muda, Dt. Sutan Maharaja sudah cukup mapan. Ini membuat dia tidak terpaut dengan tanah ulayat yang diwariskan oleh ninik mamaknya.
“…sedang hoetan tanah harta poesaka peninggalan Datoe’ Soetan Maharadja Besar jang bersawah di Kintjir Air namanja antara Soelit Air dengan Tandjoeng Balit tiadalah sekali2 koe kenang soepaja hatikoe djangan gadoek…”
Selama di Indrapura dan Pariaman, Dt. Sutan Maharaja mendalami ilmu tarekat, seperti: Samaniah, Syatariah, dan secara khusus tarekat Mim (Abdullah, 1972, hlm. 215). Pengaruh ajaran tarekat sangat kuat membentuk karakter Dt. Sutan Maharaja. Itulah sebabnya, dia sangat menolak pembaharuan yang bernuansa “fikih” yang dibawa oleh kaum modernis Islam di Minangkabau. Pada saat yang sama, dia bersahabat baik dengan ulama tua, seperti Syekh Khatib Ali (Soenting Melajoe, No. 21, 25 Juni 1920).
Pada awal tahun 1891, Dt. Sutan Maharaja berhenti sebagai jaksa di Pariaman. Alasan utamanya adalah karena janji kenaikan pangkat sebagai hoofdjaksa tidak kunjung ditepati pemerintah, sedangkan dia sudah menunggu sejak 1885. Selain itu, pada awal tahun tersebut, Dt. Sutan Maharaja menderita sakit yang memerlukan perawatan khusus. Berdasarkan surat rekomendasi dari dokter, dia mengajukan permohonan berhenti sebagai jaksa. Inilah yang kemudian menyebabkan dia disebut sebagai “Dt. Bangkik Orang Gila” karena meninggalkan pekerjaan jaksa saat sudah ada janji kenaikakan pangkat, seperti diberitakan dalam surat kabar “Neratja”. Padahal, pada 31 Maret 1891, Dt. Sutan Maharaja sudah tercatat sebagai redaktur surat kabar “Pelita Ketjil” yang kemudian, melalui dunia pers inilah, dia menuangkan pemikiran dan gerakan memajukan “Alam Minangkabau” (Soenting Melajoe, No. 33, 17 September 1920).
Sebelum menerbitkan Oetoesan Melajoe (2 Januari 1911) dan Soenting Melajoe (1912), Dt. Sutan Maharaja juga menjadi redaksi atau editor di surat kabar Warta Berita (1894-1895) dan Tjaja Sumatra (1904). Di akhir tahun 1910, dia berhenti dari Tjaja Sumatra dan menerbitkan surat kabar sendiri, Oetoesan Melajoe. Kehidupan Dt. Sutan Maharja, selanjutnya, tidak lepas dari aktifitas jurnalistik. Menjelang tutup usia, dia tetap mengurus penerbitan Oetoesan Melajoe dan Soenting Melajoe. Aktifitas jurnalistiknya benar-benar berhenti setelah sakitnya semakin parah, sehingga pimpinan redaksi diserahkan kepada anaknya yang masih kecil, Ratna Tenoen. Selain itu, penerbitan kedua surat kabar itu pun terganggu karena konflik antara Dt. Sutan Maharaja dengan isterinya yang tidak diketahui penyebabnya. Konflik keluarga ini, kemudian berlanjut ke dapur penerbitan, karena selama bertengkar dengan isteri, Dt. Sutan Maharaja pindah ke tempat percetakan, sehingga muncullah konflik dengan letter zetter yang mengatur layout surat kabar (Oetoesan Melajoe, 1 Februari 1921; Neratja, 15 Februari 1921).
Pada 24 Juni 1921, Mahyuddin Dt. Sutan Maharaja meninggal dunia (De Locomotief, No. 138, 24 Juni 1921, hal. 6). Bersamaan dengan itu, pimpinan Oetoesan Melajoe diserahkan kepada Chatib Maharadja dan Sidi Maharaja Lelo. Pergantian pimpinan ini, juga menghentikan “perang pena” yang dulu sering dilakukan oleh Dt. Sutan Maharaja. Terlebih setelah Oetoesan Melajoe bergabung dengan harian Peroebahan yang dipimpin oleh Abdoel Moeis, sehingga menjadi Oetoesan Melajoe Peroebahan. Uniknya, Chatib Maharadja pernah perang pena dengan Dt. Sutan Maharaja. Begitu juga dengan Abdoel Moeis yang dulu jadi musuhnya, justeru menjadi penerus surat kabar Oetoesan Melajoe (Oetoesan Melajoe, No. 25, 7 Juli 1921).
Perempuan Minangkabau dalam Gejolak Ekonomi Awal Abad ke-20
Pada 1908, pemerintah Belanda menghentikan sistem tanam paksa di Sumatera Barat. Kebijakan ini diambil karena sistem ini tidak berhasil bila dibandingkan dengan pelaksanaannya di Jawa. Akan tetapi, tanam paksa telah menyisakan tekanan dan penderitaan yang cukup berat bagi masyarakat Minangkabau pada abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Hanya saja, karakter masyarakat yang tidak ingin ditekan, membuat orang Minangkabau selalu menemukan jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi saat itu (Suryani dkk., 2019).
Mestika Zed menjelaskan pada mulanya, sistem tanam paksa melalui penanaman bibit kopi di Minangkabau tidak menimbulkan masalah yang berarti. Tradisi “Kopi Daun” yang hidup di tengah masyarakat Minangkabau saat itu, membentuk persepsi bahwa daun kopi jauh lebih berharga dari pada bijinya. Sedangkan pemerintah Belanda, justeru menginginkan biji kopi sebagai komoditas ekonomi. Akan tetapi, setelah orang Minangkabau mengetahui nilai ekonomi biji kopi, hasil tanam paksa bibit kopi justeru tidak diserahkan ke gudang-gudang kopi miliki pemerintah. Sebaliknya, mereka menjualnya ke daerah lain melalui pantai timur, sampai ke Singapura dan Malaysia. Cultuurstelsel, dengan demikian, memberikan keuntungan yang diinvestasikan ke sektor pendidikan dan agama (naik haji) (Zed, 2010).
Namun, sistem tanam paksa membentuk mentalitas “materialistik” yang merusak hubungan kekeluargaan, relasi sosial, dan pada ujungnya menguatkan tradisi merantau. Suatu keadaan yang disebut Mestika Zed sebagai peralihan menuju “Kapitalisme Global” (Zed, 2010).
Politik etis dalam kerangka ekonomi liberal mewarnai proses transisi masyarakat Minangkabau di awal abad ke-20. Artinya, Sumatera Barat mengalami dua corak eksploitasi sekaligus, yaitu: tanam paksa kopi (Amran, 1981, hlm. 91–115) dan perusahaan swasta (ekonomi liberal) (Asnan, 2015, hlm. 57). Dihentikannya tanam paksa kopi pada 1908 diiringi dengan masuknya arus modal yang sangat besar melalui perusahaan tambang. Dari tahun 1904-1919, setidaknya terdapat 19 tambang emas dan perak dibuka, termasuk pembangunan pabrik Semen Padang yang dimulai sejak tahun 1907 (Asnan, 2015). Padang, kota kediaman Dt. Sutan Maharaja, pada awal abad ke-20 telah menjadi layaknya “kota modern” karena telah memiliki perusahaan asuransi, hotel, klub ekskutif dan bisnis, surat kabar, dan hiburan kota.
Sejak tahun 1898, di Padang dan Bukittinggi, telah terdapat mesin perekam yang menurut Suryadi sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan kesadaran budaya di Minangkabau (Suryadi, 2003, 2010, 2015).
Perubahan besar terhadap struktur ekonomi di Minangkabau juga semakin mendorong keterlibatan perempuan di ruang publik. Kegiatan di pasar banyak dilakukan oleh kaum perempuan (Yati, 2017). Kehadiran lembaga pendidikan, keterampilan yang dibangun olehpemerintah, ulama yang pulang dari mekah, atau pun tokoh adat, menjadi ruang baru bagi perempuan Minangkabau menunjukkan eksistensinya (Yati, 2017). Ruhana Kuddus adalah tokoh sentral yang memainkan peranan penting dalam proses transformasi perempuan Minangkabau pada awal abad ke-20 (Agustiningsih, 2019). Melalui Kerajinan Amai Setia, dia tidak hanya menggerakkan perempuan entrepreneur (Hanani, 2020), tetapi juga meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan bagi perempuan di Minangkabau (Fitriyanti, 2001; Sari, 2016).
Selain melalui lembaga pendidikan dan kerajinan, gerakan perempuan Minangkabau pada awal abad ke-20 juga tidak terlepas dari peranan surat kabar. Soenting Melajoe adalah surat kabar perempuan pertama yang terbit di Minangkabau dan menjadi lokomotif gagasan dan gerekan kaum perempuan pada masa tersebut (Chaniago, 2014). Surat kabar ini didirikan oleh Mahyuddin Dt. Sutan Maharaja atas permintaan Ruhana Kuddus pada 12 Juli 1912 (Fitriyanti, 2001). Soenting Melajoe menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya bisa melakukan pekerjaan domestik (Chaniago, 2014). Tidak berlebihan bila Salmon menyebut Soenting Melajoe sebagai pers feminis (Salmon, 1977). Selain karena Soenting Melajo dikerjakan oleh perempuan (Ruhana Kuddus dan Zubaidah Ratna Juwita), tetapi juga oleh seorang feminis, yaitu: Mahyuddin Dt. Sutan Maharaja. Sebagai seorang datuk yang memahami seluk-beluk adat alam Minangkabau, Dt. Sutan Maharaja menjadi penggerak gerekan perempuan pada saat itu. (bersambung)
E-mail penulis: addiarrahman@uinjambi.ac.id