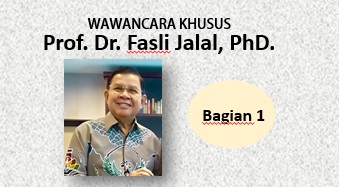Ada yang berpendapat selain pariwisata dan kuliner, pendidikan adalah sektor yang dapat dijadikan andalan bagi Sumatera Barat (Sumbar). Bahkan belakangan ini muncul perbincangan di media dari berbagai tokoh Minang bagaimana mengembalikan kesuksesan masa lalu pendidikan di ranah Minang. Budiarman dari Minang Global berbincang-bincang dengan Prof. Fasli Jalal yang lama bekerja di sektor pendidikan untuk mendapat pandangannya tentang pendidikan di Sumbar. Prof. Fasli Jalal pernah menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan sebelumnya Dirjen Pendidikan Tinggi. Prof. Dr. Fasli Jalal sekarang Rektor Universitas Yarsi, dan juga dipercaya memimpin Minang Diaspora Network Global. Pada kesempatan kali ini, Pak Fasli Jalal mengupas tentang latar belakang sektor pendidikan di Sumatera Barat, lingkungan pendidikan Sumatera Barat serta prospek Sumatera Barat untuk mengulangi kesuksesan masa lalu Sumbar di sektor pedidikan.
Kalau dilihat dari sisi sejarah orang Minang ini agak unik, diberi rahmat oleh Allah menempati sebidang surga di bumi, tidak luas, tapi komplit. Ada gunung, laut, danau, hutan, lembah. Keunikan itu membuat komunitas Minang harus cerdas dalam kehidupannya. Kalau kita lihat adat di Minangkabau, setiap suku itu dibagi lagi ke rumah gadang, ada datuak.
Di setiap rumah gadang itu ada lima yang harus diamankan. Pertama, pangan, tidak bisa ditawar. Meskipun perang, beras tetap harus ada. Karena itu masalah sawah dengan segala ramifikasinya menjadi penting dan itulah orang Minang, pangan harus tersedia sebagai bentuk bantuan sosial kita kepada orang banyak. Makanya harus ada satu rangkiang yang khusus untuk bisa diambil padinya untuk memberi makan orang yang lewat.
Kalau zakat muncul belakangan, i Minang pangan itu bentuk zakat pertama sehingga yang ada di rangkiang itu diberikan. Ini menjadi pertanyaan bagaimana mengaitkannya dengan pendidikan. Jaminan ketahanan pangan keluarga dan pada akhirnya komunitas.
Kedua, dengan segala kesempitannya setiap rumah gadang itu ada kebun. Kebun itu bentuk kacio (tabungan), bisa tanam jengkol, petai, buah-buahan, lansek, jeruk, tanaman-tanaman yang tahan lama. Kebun menjadi bagian dari keluarga Minang, wajib memiliki kebun. Tinggal menentukan apa yang dibutuhkan untuk ditanam di situ. Di atas terjaminnya pangan tadi, dari kebun inilah di supplai tambahannya kalau ada anak sekolah, memperbaiki rumah dan lainnya.
Untuk sehari-hari kita sudah canggih gizinya, ada tabek (kolam), tabek yang di darat, kalau tabek di pantai sudah jelas, besar di tepi laut. Kalau di luak di ateh kan selalu ado tabek, dari tabek inilah sumber protein, baik untuk harian maupun mingguan. Kalau tabeknya agak besar hasilnya bisa dijual untuk mendapatkan uang kontan.
Biasanya dijual di balai mingguan, di kampung saya balai Kamis. Itulah kesempatan bertransaksi sehingga di atas ketahanan pangan, adanya kacio tadi untuk pendapatan yang lebih besar untuk keseharian, tapi untuk protein dan jaminan, ditambah satu lagi yaitu dengan ternak. Orang Minang selalu mempunyai ternak, ayam atau itik, sapi, kambing, kerbau. Itulah yang dipakai untuk baralek, peristiwa yang besar. Tinggal dilihat mana yang dibutuhkan, mulai dari ayam sampai kerbau.

Jadi yang empat itu sudah menjadi bagian penting dari ekonomi orang Minang, ditambah lagi dulu itu, saya masih mengalami adanya semacam gentlemen agreement di komunitas kita itu untuk berbagi pekerjaan handycraft. Kita sudah membagi dengan agak serius siapa yang membuat pisau, sabit, dan lainnya, itu agak serius industri rumah tangganya.
Ada yang membuat ukiran, bordiran. Di rumah, uni saya dan etek saya membuat tikar anyaman. Itulah yang menghasilkan uang kontan bilamana dijual pada hari pasar, Kamis. Jadi sejak hari Minggu kami sudah menyiapkan barang-barang tersebut, dan Rabu malam siap untuk dijual besoknya. Dengan itulah dibeli gula, garam, minyak yang tidak bisa diproduksi sendiri.
Pertanyaan sekarang, bagaimana kita memahami pola kehidupan ini untuk Sumbar yang semakin tertatih-tatih. Karena untuk pertanian air mungkin sulit, harga saprodinya (saran produksi pertanian) semakin mahal, tidak tersedia pada waktunya. Air karena terpengaruh climate change. Dulu bagus sekali dan ada aturan sosial yang ketat sehingga pembagian air itu dijaga keadilannya, dan kalau ada bentrokan fisik, cepat diambil alih oleh lembaga adat untuk mencari solusinya.
Rujukannya jelas, misalnya pembagian air sungai itu untuk membaginya ada alat yang diambil dari papan, bukan dari beton tapi dari papan sehingga bisa di-check setiap saat kalau ada yang mengubahnya. Itu tidak terjadi sekarang. Sekarang, kita dari sisi keluarga-keluarga, walaupun secara daerah masih mengekspor beras, tapi keluarga kita sudah makin banyak yang kesulitan mendapat beras, dan sekarang mulai membeli.
Kalau dia mempunyai paket pertanian, nilai tukar semakin rendah. Saya ingat dulu waktu masih kecil, kalau menjual satu sumpik padi (kira-kira 20 liter) kita bisa plesir ke Padang dari Lintau, berangkat subuh-subuh, menonton dulu jam 10.00 pagi (matinee) di bioskop Raya, kemudian makan bubur kampiun, habis lohor menikmati pantai sambil makan sate, jam 5 sore kembali lagi baru sampai tengah malam di Lintau. Itu hanya dengan satu sumpik saja.
Sekarang satu sumpik saja untuk bayar transport tidak cukup. Jadi terjadi penurunan yang besar dari nilai tukar itu.
Orang dulu dengan cara hidup seperti ini, anak-anak kita dididik harus pandai di lima bidang ini, life skill jadi penting. Itu pelajaran terpenting, “Alam Terkembang Jadi Guru”, karena itu nyata dan sehari-hari. Jadi kalau anak diminta berinovasi, apakah inovasi itu di pertanian, peternakan, perikanan dalam konteks ini sumber protein yang tidak jahat.
Dulu daging merah (white meat & red meat) menjadi isu di kesehatan, di kita sudah dari dulu selesainya isu itu. Kapan makan yang red meat itu sekali-sekali saja, tapi yang sehari-hari itu, kalau tidak ayam, telur, atau ikan. Itu sehat sekali. Tidak disadari itulah kebiasaan-kebiasaan kita. Dulu, orang menyalahkan santan. Prof. Indrawati membuktikan bahwa santan itu tidak sejahat minyak.
Jadi, sebetulnya canggih budaya kita ini, dan waktu itu setiap sekolah memberi kesempatan kepada anak-anak untuk memilih apa bidang yang ia minati, bagaimana ia berporses untuk berpindah-pindah. Karena ada saja anak-anak kita di rumah yang suka sawah, ternak, perkebunan. Itu sudah dibangun oleh kultur kita agar anak harus belajar dari alam, harus mengerti lima pilar ini bahwa pangan harus kuat bermartabat, kemudian harus ada tabungan yang setiap saat untuk kemandirian dari upaya kita sendiri.
Menanam itu kan kadang-kadang bertahun-tahun, cengkeh enam tahun baru berbuah. Tapi orang minang tahu bahwa ini kacio, dan anak-anak sudah dididik untuk itu. Sekolah kita ketika itu memungkinkan. Jadi guru-guru kita bisa membawa bakat anak-anak itu dilihat dari yang tadi, ada dari basic, ada inovasi dan kreativitas yang sekarang sedang kita cari-cari.
Nah, pada waktu mulai orde baru, itu yang paling berat sebenarnya. Pada zaman Belanda minat kita luar biasa karena disamping Politik Etis Belanda, orang Minang mendapat privilege ketika itu, terutama Kotogadang, Lintau , dan beberapa lagi mendapat kesempatan di sekolah-sekolah terbaik, konsentrasinya lebih banyak dan dipercaya mengelola sekolah-sekolah Belanda. Sekolah Raja itu ada empat, satu di Sumbar dan di Jawa, dan belakangan ada di Sulawesi Utara dan NTT .
Jadi betapa besar manfaatnya, tentu karena ada di lokasi kita, orang-orang kita lebih banyak dapat kesempatan secara disproporsionate, tapi juga menerima orang-orang asing. Dengan demikian multikultural itu sudah terbentuk sejak di Sekolah Raja itu.
Kemudian orang-orang kita mengajar ke mana-mana dan mereka menjadi tokoh di mana mereka mengajar. Jadi muncul wajah Minang yang terdidik, kultur yang betul-betul ramah dengan alam, mengerti cara mengatur kehidupan sosial. Petatah petitih kita itu kan sebetulnya kaya dengan pesan. Kalau kita merantau, menyauak di bawah-bawah, mangecek merandah-randah. Jangan kita di rantau merasa bos, harus pandai-pandai, kapan kita bicara, jangan potong rejeki orang, ada saja usaha orang yang sudah tradisional dikerjakan karena kita lebih pintar. Itu membuat kita relatif diterima di mana-mana.
Tapi model kita tadi selain lima pilar itu, adanya surau tempat exercise, dia lembaga agama tapi tidak dibuat sakral, dibuat bebas. Sehingga orang merasakan ruh agama ada, tapi bisa mengekspresikan diri secara bebas, bersilat, olah raga, kesenian, berdebat, apa saja bisa. Kegiatan yang agak kurang diterima di masjid, di surau dibebaskan.
Surau menjadi tempat yang menarik untuk pendidikan sosial bagi anak-anak kita, saya masih sempat merasakan. Sore kami jam lima sudah ke surau, makan terakhir jam lima, dan kemudian sholat maghrib dan kami berbagi tugas, imamnya tentu gurunya, ada yang azan, dan makmum dan kemudian mengaji.
Ada yang tahap belajar awal, ada yang sudah menjadi instruktur, ada yang sudah menjadi mentor. Semacam training center, di mana ada yang suka mengaji, azan, pidato. Kultum itu dulu sudah diajar di surau. Ada yang sukanya silek, olah raga lain seperti bola kaki, kasti dan lainnya. Setiap pagi hari Minggu, ada makanan kemudian kita bergotong-royong lebih dahulu, kegiatan sosial, membersihkan masjid, jalan di sekitar kita dan sebagainya. Jadi tanggung jawab sosial kebersihan luar biasa masa itu. Itu kan sebagian dari iman. Orang Minang sebetulnya bersih hidupnya. Setelah itu boleh memilih mau akivitas apa, mengaji, olah raga, silat.
Saya melihat, model itu yang menghasilkan petinggi-petinggi Minang dulu, di samping mendapatkan pendidikan Barat seperti Hatta, Sjahrir, sebetulnya sudah memiliki basis yang kuat, kan sama-sama berpendidikan Barat dengan orang Jawa dan lainnya. Basis yang kuat sudah terbangun membuat tumbuh kreativitas, inovasi, kemandirian.
“Alam terkembang menjadi guru,” pastikan lima pilar ini, anda berkreativitaslah dengan segala kecanggihan, pada akhirnya urusan ekonomi semua ini, tapi jangan lupa kita ini orang Islam yang ruhnya di surau, tapi untuk ritualnya ke masjid yang memang agak sakral dan di masjid tidak banyak training, pendidikannya agak searah. Di surau boleh dua arah, bisa “bertengkar” dengan guru, dan mentor kita boleh kita challenge karena mereka kayak kita dulunya. Di masjid tidak bisa begitu.
Ditambah lapau di mana perdebatan-perdebatan terjadi, dan kita mula-mula mendengar dulu siapa yang pandai berdebat, lalu sekali-sekali mulai menyela dan baca-baca kalau ada topik yang terbaru, itupun dari radio pada tahun 60-an. Cara kita dididik yaitu, di surau, di lapau, dan lima pilar itu.
Selain di rumah, di nagari itu kita kan punya dangau yaitu tanah di mana ada kebun, ada sawah. Kalau suku-suku yang kaya, mereka punya sawah di sekitarnya. Tapi suku-suku yang berkembang mereka menaruko namanya, membuka hutan, membuat sawah atau ladang baru. Jadi di sana ada rumah sementara yang disebut dangau. Jadi, kita tumbuh di surau, di dangau dan di lapau. Ini tempat kita berinteraksi dengan masyarakat, mendengar isu apa, melihat cara berdebat, diksinya dan lainnya.
Sampai masa Sukarno, itu masih terjaga, tapi masuk Orde Baru karena rejim militer, kesamaan, uniformitas itu penting. Jadi semua yang diajarkan itu wajib diikuti. Tidak ada ruang gerak bagi kepala sekolah, para guru. Dulu sekolah dengan masyarakat itu menyatu. Nah lalu dipisah, tidak boleh lagi acara-acara masyarakat di sekolah.
Sejak itu mulailah sekolah-sekolah kita kedodoran untuk melahirkan anak Minang seperti semula itu. Waktu itu guru-gurunya dididik dalam suasana seperti itu. Lahirlah sekolah-sekolah dasar Inpres dengan guru yang dikarbit. Saya pernah lihat data, di Sumbar tidak terlalu banyak, tetapi di daerah-daerah lain untuk mengajar SD, lulusan SD dilatih enam bulan bisa menjadi guru SD. Di kita waktu itu yang paling rendah di SMP karena SD Inpres banyak, sedangkan lulusan SGA-nya tidak banyak, jadi dikarbitlah guru-guru itu.
Di satu pihak Pak Harto bagus karena membangun SD Inpres di mana-mana, tapi kita mulai mengorbankan mutu, dan itu di dalam sistim yang otoriter yang tidak memberikan ruang gerak sehingga berlepotanlah sekolah-sekolah di Sumbar itu, INS, Adabyah, Tawalib karena mereka harus memilih. Kalau tidak mengikuti itu, tidak boleh ujian nasional, tidak diberi ijazah untuk melanjutkan.
Dulu ijazah itu tidak terlalu penting benar karena orang bisa ke Mesir, ke Gontor, bisa diterima sekolah hanya dengan selembar surat (rekomendasi), seperti kakak saya, karena guru dia mahasiswa Gajah Mada yang ditugaskan mengajar di mana-mana, dengan selembar surat rekomendasi darinya, dia bisa masuk Gajah Mada. Jadi, rekomendasi berperan. Artinya bukan selembar ijazah yang berisi nilai-nilai yang kadang-kadang bisa di karbit, tetapi yang dilihat siapa manusianya ini. Memang tidak gampang pula memberi rekomendasi kalau tidak tahu anak itu dari kelas satu sampai kelas tiga.
Pendek kata kita memang mengalami kehilangan banyak karena ada perubahan ekosistem selama 32 tahun. Reformasi harusnya bisa mengembalikan, tapi karena sistemnya sudah terbangun dan guru-guru kita sudah berada di dalam sistim seperti itu. Jadi kita harus brain washing guru-guru kita itu, dan itu almost impossible. Empat juta orang yang dididik seperti itu, masuk di dalam sistem dan berlama-lama di sistem itu. Ini sementara mempengaruh juga LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), IKIP-IKIP- nya, jadi tidak bisa lagi meniru gaya sekolah raja.
Waktu program B di Dikti, kalau A di SMA, B di SMP, itu sebenarnya tidak terlalu akademik, lebih vokasi tapi professional. Dulu guru-guru SGA kita mengajar guru SD kan boarding, jadi memang guru-guru SD itu, meskipun guru SGA itu selevel SMA, tapi mereka anak-anak SMP terbaik dimasukkan SGA boarding. Mulai dibayar TID-nya (Tunjangan Ikatan Dinas). Kalau pulang pakai sepeda, mereka terpandang sebagai guru, jadi mengidolakan guru luar biasa masa itu. Tapi waktu itu kita kan pendidikan kita masih elitis, belum masif. Kita tidak bisa elitis terus karena APK kita masih rendah, yaitu angka partisipasi kita di SD.
Pertanyaan besar apakah bisa kita di Sumbar mencoba membersihkan kerak-kerak selama 32 tahun masa Orba itu? Sebenarnya di masa Menteri Nadiem, sebetulnya kita punya peluang, sedikit. Cuma dia komunikasi publiknya kurang. Jadi dia dihantam oleh pemda karena dianggap sangat otoriter, memaksakan saja. Dia tidak ramah dengan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dan perguruan tinggi, dan dia sangat elitis, dia sangat yakin dengan programnya.
Dia punya empat-ratus orang anak-anak muda lulusan Harvard, MIT dan lainnya yang jadi shadow government dia. Jadi isu terbaik dunia, dia dapat, dan dia bisa buat konsep dengan cepat, dia paksakan. Kalau Dirjennya tidak bisa, dia dampingi dirjennya dengan satu orang yang mengejar Dirjennya kalau rapat. Sebetulnya sayang karena ada Covid dua tahun. Kalau Nadiem bisa bekerja dua periode, sepuluh tahun, pendidikan kita bisa bayak berubah, ada dampaknya.
Saya berpendapat kepada teman-teman, sekarang begini saja, walaupun menteri baru, kalaupun segala yang dilakukan Nadiem itu tidak, menurut saya kita lihat saja mana yang bagus-bagus, kan guru-guru kita tahu. Nama tidak usah, tiru saja kalau namanya deep learning, lupakanlah kalau mereka belajar itu, tapi pindahkan diksinya ke deep learning, tapi esensi yang bagus-bagus itu yang guru tahu, pakai, saya bilang. Mulai masukkan nuansa-nuansa lokal itu. Jadi itulah tantangan kita sekarang.
Budiarman: Adakah kemungkinan kita sedikit menyimpang dari sistem nasional sekarang. Tapi bisa ditolerir oleh sistem.
Sebenarnya mereka belajar itu, jadi bayangkan, umpama mahasiswa, diberikan 40 SKS setahun di luar kampus. Mau magang-kah, serius benar mau mendalami apa yang terjadi di masyarakat. Misalnya mahasiswa pertanian, dia bisa melakukan siklus pertanian itu, penuh dan dikasih SKS. Dulu-kan sebentar icoba di green house dan sebagainya. Jadi tidak komplit dan kadang-kadang terlalu di simulasi di dalam setting yang relatif steril. Padahal pengalaman lapangan itu penting di bidang apapun, di bidang konstruksi, engineering, di bidang pendidikan, ekonomi, pertanian, kesehatan. Nah itu dimungkinkan oleh program ini.
Pada mulanya dosen kita banyak yang menolak karena mereka ragu-ragu, 40 SKS itu seimbang nggak nanti didapat dari masyarakat. Tapi orang Minang sudah membuktikan belajar dari alam jauh lebih dahsyat daripada belajar di lingkungan sekolah, dan kadang-kadang dosennya juga tertinggal ilmunya. Apalagi sekarang, anak-anak bisa sangat canggih.
Cuma dia kan harus di-expose dengan kenyataan. Makanya sekarang project based learning, atau objective based education. Jadi harus ada masalah-masalah yang jelas diberikan kepada mereka dan dampingi mereka bagaimana caranya melihat pendekatan solusinya dari lintas ilmu, kemudian bagaimana berinovasi dalam proses itu serta percaya diri untuk mengambil rencana dan mencoba bahwa ini solusi yang dia ambil dari beberapa altertif yang dia pilih dan paling mungkin berhasil. Kalau gagal, dia belajar dari itu.
Nah kalau ini bisa kita capitalize di Sumbar, saya agak optimis karena DNA kita masih ada, cuma sekarang guru dan dosen. Waktu Covid, kami dari Minang Diaspora menjangkau sampai 11 ribu guru untuk melatih mereka, dari nggak tahu IT sama sekali karena selama Covid dia-kan harus mengajar dengan IT. Bahkan ada yang tanya apa itu PPT, belum lagi menggerakkan mouse saja nggak tahu dia. Kita latih mereka enam bulan. Saya ajak Dirjennya waktu itu, Iwan Syahrir, untuk membuka. Guru-guru kita itu sudah sangat birokratis, jadi lingkungan terdekatnya tidak terlalu penting bagi dia karena rujukannya dia harus patuh kepada yang di atas. Jadi wajah orang di atas, perintah orang di atas, kedatangan orang di atas sangat penting. Itu segala-galanya ketimbang mereka menanyakan mencari solusi lokal, berani mencoba. Itu sudah hilang.
Budiarman: Apakah itu terjadi juga di sekolah swasta ?
Termasuk, karena swasta harus mengikuti juga kurikulum nasional, diuji dulu, ujian nasional. Nah, Mas Nadiem ini membuka. Makanya kami mencoba juga bereksperimen di INS. Memang belum berhasil karena begitu kita menyebut nama SMA, orang sudah mempertanyakan bisa nggak diterima di ITB, di UI, di Gajah Mada. Itu lebih dahulu pertanyaannya. Padahal di INS itu, pertama di hati lebih dahulu. Jadi memang emosional, spiritualitas harus kuat. Jadi pembelajarannya harus mementingkan spiritualitas dan kekuatan emosional. Kematangan. Kemudian baru pikiran, intelektualitas.
Tapi, yang dua ini saja tidak cukup, harus kreatif. Kreativitas itu harus ditunjukkan dengan tangan. Jadi tangan kita ini tidak boleh berhenti melakukan apa saja, mau main musik, melukis, tanam ini, tanam itu, mau jualan, mau buat handycraft, jangan berhenti, apapun yang anda senangi. Di sana dasarnya kasih tanah liat, boleh buat apa saja. Jadi umpama mulanya membuat pot bunga, itu bisa menghasilkan macam-macam karena kreatif, dan orang terheran-heran dengan kreativitasnya. Guru sekarang bisa marah-marah dia karena diberi contoh begini, yang lain jadinya.
Di sana itu dimungkinkan. Jadi, kadang-kadang asbak ini saja (sambil menunjuk ke sebuah asbak) bisa dibuat macam-macam, berbentuk kapal dan lainnya. Pada waktu itu tanah liat sudah tersedia, paling-paling mengolah, kemudian membakarnya dan memberi sedikit warna. Maksudnya, yang mulanya rencana membuat ini, bisa lari kemana-mana, dan itu dibenarkan, asal ada rasionalnya. Kenapa anda membuat itu, apa dasarnya, apa azas kemanfaatan. (Bersambung ke bagian kedua)
Penulis: Budiarman Bahar